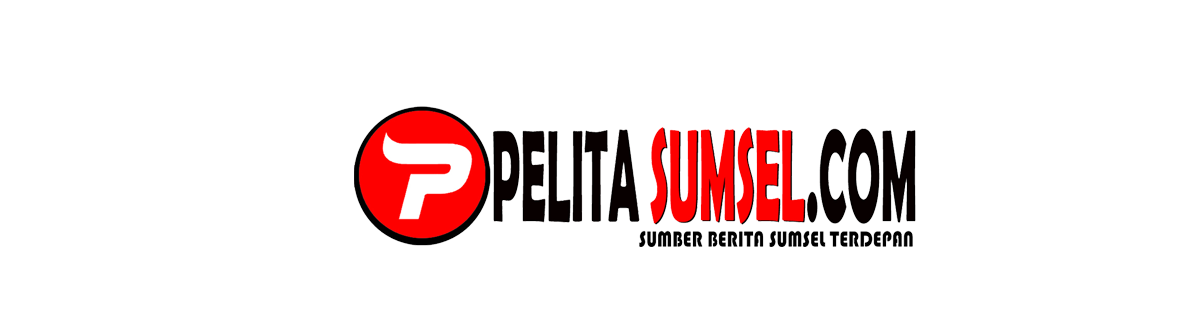Palembang, Dua Dasawarsa Pasca Revolusi Fisik

 0
0
Oleh :
Arafah Pramasto,S.Pd.
(Anggota Studie Club ‘Gerak Gerik Sejarah’)
Kota tertua di Pulau Sumatera, Palembang, kerap mengambil peranan penting di dalam potongan-potongan fase kesejarahan daerahnya, maupun dalam lingkup yang lebih luas. Telah cukup kita banyak membaca bagaimana berita-berita Cina yang mengabarkan mengenai eksistensi kota ini, belum lagi yang membatu dalam prasasti-prasasti di era Sriwijaya. Begitupun untuk era-era berikutnya yakni pada masa awal Islam, kesultanan, sampai era kolonial. Ingatan atas keberadaan Palembang dengan berbagai citra / gambaran, entah dari mereka yang berasal dari kota ini maupun yang diungkapkan oleh para pengunjung, kebanyakan memuat berita-berita yang menarik. Di luar masalah “kemenarikan” yang mungkin dikarenakan narasi dalam cerita-cerita tertentu berisi kejadian luar biasa, sesungguhnya yang lebih penting ialah bagaimana informasi-informasi itu dapat membangun kognisi kita atas kondisi di masa silam dalam konteks pengabadian sejarah.
Sebagai salah satu kota besar era kolonial, Palembang tidak bisa mengelak dari berbagai dinamika penting dalam sejarah bangsa ini. Termasuk di antaranya ialah saat bergulirnya proses kemerdekaan bangsa Indonesia yakni di kala pecahnya Perang Pasifik, Proklamasi, hingga Revolusi Fisik. Cerita-cerita heroisme, kemiliteran, dan manuver-manuver politik di dalamnya dapat dengan mudah ditemukan dalam berbagai penyajian tulisan oleh para ahli maupun pemerhati kesejarahan Palembang. Dalam tulisan sederhana ini penulis ingin sedikit mendedahkan ulasan tentang kota yang kesohor dengan kuliner pempeknya, tidak dari sudut pandang para pelancong ataupun kajian ilmiah, melainkan yang terekam dalam sumber-sumber tulisan yang meski dapat dibilang ringan namun tak ada salahnya kita baca kembali. Lingkup waktu yang diambil bukan pada era perang Revolusi Fisik (1945-1949), namun pada sekitar dua dekade setelahnya.
Tentang Masyarakat, Hiburan, Ekonomi, hingga Kepercayaan
Apa yang terjadi pada Palembang pasca usainya Revolusi Fisik ? Antologi karangan Rd. Muhammad Ikhsan, penulis kesejarahan Palembang, yang berjudul ‘Palembang dari Waktoe ke Waktu’ melukiskan bahwa kota ini pada era 50-an masih terasa sepi dan lengang dengan jumlah penduduk sekitar 400 ribu jiwa. Secara etnologis suku bangsa Palembang meliputi 50% penduduk kota, di samping suku-suku Indonesia lain seperti Tapanuli, Minangkabau, Jawa, dan pedalaman Palembang. Selain itu orang Tionghoa, Arab, India (seperti pemilik merk dagang Martabak HAR), dan bangsa barat lain di antaranya Amerika, Eropa, terutama Belanda, juga menetap dan mencari hidup di sini. Tidak berlebihan jika pada era ini ciri sebagai kota “Melting Pot” atau “Panci Adukan” dari berbagai suku bangsa dan keturunan mulai terbangun.[1]
Tulisan Rd. M. Ikhsan tersebut cukup beralasan dan memiliki kesesuaian dengan sumber lain yang sezaman dengan lingkup waktu tersebut. Buku berjudul ‘Ilmu Bumi Sumatera dan Tanah Air Kita Indonesia’ karangan M.D. Adiwikarta yang disetujui “Konferensi Dinas Penilik2 SR (Sekolah Rakyat) dan Penilik2 Kepala SR” tanggal 8-10 Januari 1953 sebagai buku pegangan siswa SR kelas V, menyebutkan bahwa Palembang yang menjadi ibukota ‘Daerah Swatantra Sumatera Selatan’ – meliputi pula Bangka Belitung, Lampung, dan Bengkulu – jumlah penduduknya “…belum dapat dikatakan tjukup, apalagi padat. Ini disebabkan banjaknja bagian2 jang tak dapat didiami, jaitu daerah2 rawa… Penghidupan rakjat pada umumnja tidak menghawatirkan, bahkan mendekati sedjahtera…”[2] Agaknya, gambaran mengenai penghidupan (perekenomian) dari warga kota yang “mendekati sejahtera”, sebagaimana dalam tulisan Adiwikarta, terlihat dari cara mereka menikmati hiburan di kota ini, yang paling utama adalah bioskop. Rd. M. Ikhsan menyebut sekian nama bioskop di kota ini seperti Capitol, Initium, International, Lucky, Majestic, Merdeka, Persatuan, Rex, dan Saga. Tidak heran jika setiap sore hingga malam hari, orang ramai mengantri di muka loket untuk menonton film.[3]
Soal keberagaman etnis di kota Palembang pada era 1950-an itu, sesungguhnya tidak tergolong fenomena baru. Apabila sekarang terdapat segolongan orang yang kerap melontarkan kebencian pada orang asing maupun pada kelompok yang mereka sebut “Aseng”, sepertinya mereka tidak mempelajari sejarah bangsa ini, utamanya mengenai kota Palembang. Buku berjudul ‘Zaman Silam’ yang digunakan selama 22 tahun di sekolah-sekolah dasar Indonesia (1953-1975) karangan Soeroto (wartawan senior dan mantan dosen SSKAD), mengungkap bahwa dahulu, kapal-kapal yang bertolak dari pelabuhan di Cina sering singgah di Kerajaan Sriwijaya, di sini mereka mengisi air minum, dan membeli bekal makanan sambil menunggu angin baik, sebelum meneruskan perjalanan ke India. Dalam penantian itu terkadang mereka harus tinggal berbulan-bulan di ibukota Sriwijaya (Palembang-Pen).[4] Keterbukaan serta kadar pluralitas Palembang sudah dipupuk sejak lama, dan terus bertahan sampai sekarang. Mereka yang berasal dari negeri asing ataupun para keturunannya, bukan hanya dapat singgah, melainkan pula bisa mencari nafkah di tanah ini.
Masa setelah perang kemerdekaan itu pun dapat dibilang sebagai masa pembentukan kesadaran kebangsaan yang cukup baik dan di kota Palembang-lah salah satu mikrokosmis dari kemunculan paradigma itu. Kembali merujuk dari pendapat Rd. M. Ikhsan, dari bermacam suku bangsa yang hidup di kota ini, mereka tidak lagi membawa simbol kedaerahan yang justru menjadi satu dengan sebutan “Wong Palembang” atau “Wong Kito.”[5] Hal ini dibuktikan juga dengan apa yang terjadi di tengah komunitas Jemaat Gereja Kristen Jawa (GKJ). Pada sidang klasis bulan Juli 1958, GKJ menerima usul penggunaan bahasa Indonesia bagi jemaatnya di Palembang. Alasannya, sebagaimana termuat dalam buku ‘Peringatan 20 Tahun Gereja Kristen Palembang “Siloam”‘ ialah, “… Mengingat situasi lingkungan di kota Palembang, untuk menghilangkan prasangka negatif yaitu perasaan propinsialisme dan sukuisme serta perkembangan bangsa setelah merdeka, dimana bahasa persatuan dan bahasa nasional adalah bahasa Indonesia, maka penggunaan bahasa Jawa dirasa kurang memenuhi kebutuhan dan kelancaran tugas-tugas perawatan dan pemeliharaan Jemaat…”[6]
Sekalipun terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang beragama lain dengan kebanyakan warga Palembang yang mayoritas memeluk Islam, era setelah kemerdekaan di kota ini sangat minim konflik. Keislaman tersebut juga memiliki sedikit dimensi yang berkaitan pula dengan aspek profesi dalam masalah ekonomi. Adiwikarta menuturkan, “…Disamping bertani, orang2 Palembang lebih terkenal sebagai pedagang-pedagang jang tangkas, ulung, dan hemat-tjermat. Oleh karena itu, tidak sedikit diantara mereka jang mendjadi kaja-raja. Dari orang2 Palembang itu terkenal pula kepatuhannja kepada agama Islam…”[7] Membaca uraian itu tentu mengingatkan penulis tentang kisah hidup Rasulullah Saw, yang mana beliaupun dahulu pernah hidup dengan bermata pencaharian sebagai seorang pedagang yang sukses. Bisa dikatakan, orang Palembang tidak hanya menerapkan Islam dari sisi ibadah namun juga mengambil inspirasi keagamaan sebagai jalan hidupnya.
Sungai, Transportasi, dan Pendidikan
Dada Meuraxa, penulis buku ‘Keradjaan Melaju Purba’ tahun 1971 bercerita dalam bukunya saat menyusuri Sungai Musi dalam sebuah perjalanan menuju kota Palembang. Dada berusaha membayangkan bagaimana di era dahulu jung-jung (Kapal) Cina dan negeri tetangga meramaikan sungai Musi untuk berdagang dengan Sriwijaya, seperti saat kapal yang ia tumpangi sering berpapasan dengan “…tankker2 raksasa kepunjaan segala bangsa untuk mengambil minjak ke Sungai Gerong dan Peladju…”[8] Setibanya di kota Palembang, sang penulis tertarik dengan museum Palembang, utamanya koleksi berupa, “… satu kemudi kapal zaman Purba besar sekali. Bila kita perhatikan besarnja kemudi itu teranglah ratusan tahun jang lalu kapal2 Seriwidjaja ada djuga jang berukuran 100 ton, lebih besar dari kapal motor jang saja tumpangi hanja berkekuatan 60 ton sadja…”[9]
Koleksi kemudi kapal yang dimaksudkan dalam tulisan Dada Meuraxa di atas adalah salah satu koleksi yang hingga sekarang masih tersimpan di Museum Sriwijaya yang terletak di kawasan Gandus, Kota Palembang. Koleksi ini adalah masterpiece pembuktian Kerajaan Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan maritim besar. Kemudi kapal ini terbuat dari kayu unglen atau biasa disebut penduduk dengan sebutan “Kayu Besi”, karena jenis kayu ini jika sering terendam dalam air akan semakin kuat. Kemudi ini mempunyai panjang 8,2 meter, ditemukan di daerah Sungai Buah Palembang pada tahun 1960. Kemampuan maritim Sriwijaya hingga mampu menjelajah perairan Nusantara, kawasan Asia hingga ke Madagaskar tidak terlepas dari kemampuan teknologi pembuatan kapalnya. Kapal-kapal Sriwijaya telah mampu membawa saudagar beserta barang-barang dagangannya, tentara beserta persenjataannya, dan yang lebih penting adalah membawa budaya antar-bangsa.[10]
Tidak lengkap rasanya jika berbicara soal kota Palembang beserta sejarah transportasi sungai, tanpa mengingat sebuah sarana transportasi yang ikonik bagi kota ini : Jembatan Ampera. Dada Meuraxa menyebutkan bahwa salah satu kebanggaan Palembang adalah, “…djembatan Amperanja mendjulur menjambung dua kota jang dibelah Sungai Musi itu…”[11] Benar saja, tanggal 10 April 1962 adalah hari penting yakni pembangunan sebuah jembatan yang melintasi Sungai Musi, dimulai pada tanggal 10 April 1962 dan selesai pada tahun 1964. Upacara permulaan pembangunan Jembatan Ampera (sebelumnya pernah diberi nama “Jembatan Sukarno”) dihadiri langsung oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Sukarno. Jembatan yang kemudian diberi nama “Ampera” ini sangat penting artinya bagi kelancaran lalu lintas dan perekonomian daerah Sumatera Selatan umumnya, kota Palembang khususnya.[12]
Walaupun telah sejak lama Palembang identik dengan peradaban sungainya, bukan berarti pada masa setelah perang kemerdekaan, bidang-bidang transportasi lainnya tidak beroperasi dengan baik. Sebaliknya, pada era 1950-160an, hubungan transportasi Jakarta-Palembang baik sekali dan ramai pula. Di Palembang telah ada Bandara Talang Betutu yang pembangunannya sudah dimulai sejak tahun 1920,[13] ejaan zaman kolonial dahulu adalah ‘Talang Betoetoe.’ Adiwikarta menjelaskan bahwa untuk hubungan (transportasi) cepat dengan biaya tinggi dapat menumpang pesawat terbang G.I.A (Garuda Indonesia Airlines) yang menempuh jarak itu (Jakarta-Palembang) dalam waktu 13/4 jam saja. Trayek G.I.A melayani beberapa rute diantaranya, Jakarta-Palembang-Jambi, Jakarta-Palembang-Pekanbaru-Medan, dan Jakarta-Palembang-Singapura. “…Lapang-terbang Palembang letaknja di Talangbetutuh, agak djauh dari kota Palembang sendiri. Lapang terbang itu sudah menpunjai landasan “Convair”. Artinja dapat dipakai untuk pendaratan pesawat2 besar “Convair”…”, tulis Adiwikarta.[14]
Pilihan lain di samping transportasi udara dari Jakarta ke Palembang, ialah moda angkutan kereta api. Untuk penumpang biasa atau umum dapat menumpang kereta api dengan karcis langsung. Perjalanan menggunakan kereta api dari ibukota menuju kota pempek pada zaman itu digambarkan sebagai berikut :
“…berangkat dari Djakarta djam 6.00 sampai ke Merak kira2 djam 10.30, lalu dengan kapal ketjil menjeberangi Sel. Sunda selama 5 1/2 djam, sampai ke Pandjang djam 17.00. Setelah menginap di Tandjungkarang, perdjalanan dilandjutkan esok harinja. Perdjalanan kereta-api Tandjungkarang-Kertapati (k.a. tidak sampai ke Palembang) memerlukan waktu kira2 9 1/2 djam (berangkat djam 7.30 sampai djam 16.30)…Hubungan k.a. ada pula antara Lubuklinggau-Prabumulih-Palembang…”[15]
Meski dalam beberapa bidang yang telah disebutkan di atas kota Palembang mendapat apresiasi, Dada Meuraxa dan Adiwikarta menilai ada sejumlah bidang yang belum dapat dibilang baik. Pada kunjungannya, Dada Meuraxa menilai bahwa, “…Kota Palembang baru sadja mulai dibangun, djalan2 mulai diaspal. Gedung2 pemerintah dibanding dengan Medan, Palembang masih ketinggalan…”[16] Di samping masalah infrastruktur pemerintahan, Adiwikarta menuliskan,“…Kemadjuan dalam bidang pendidikan sekolah tampaknja sederhana sadja. Demikianlah sekolah tinggi baru terdapat dikota Palembang, jaitu Fakultas Ekonomi “Sjakhyakirti”…”[17]
Pernyataan mengenai kemajuan yang “sederhana” di bidang pendidikan itu nampaknya perlu dikoreksi. Buku ‘Ilmu Bumi Sumatera dan Tanah Air Kita Indonesia’ karangan Adiwikarta, meski telah memasuki cetakan ke-22 pada tahun 1961, nampaknya tidak mengalami revisi dalam substansinya. Karena pada tahun cetakan tersebut, Palembang dan Sumatera Selatan sudah mempunyai sebuah universitas yang mengabadikan nama besar kerajaan Nusantara di zaman lampau. Dimulai dari keinginan tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Selatan dan Palembang yang dinyatakan pada perayaan kemerdekaan ke-7 (1952), berdirilah Perguruan Tinggi Syakyakirti tahun 1953, akhirnya tanggal 3 November 1960 diadakan upacara penandatanganan piagam pendirian Universitas Sriwijaya (UNSRI) oleh Presiden Sukarno dengan disaksikan oleh menteri pengajaran Mr. Priyono, serta pengangkatan drg. M. Isa sebagai presiden (Rektor) pertama UNSRI berdasar Keppres No. 696/M tanggal 29 Oktober 1960.[18]
Penutup dan Makna
Mencari gambaran mengenai kota Palembang dari berbagai sumber bisa saja dilakukan, termasuk yang terekam dalam tulisan-tulisan ringan namun dapat menjadi referensi yang mampu memperlihatkan bagaimana pandangan atas kota ini terbentuk. Cukup terlihat bagaimana Palembang tak bisa lepas dari predikat “plural” dan keterbukaannya.
Transportasi sungai yang telah sejak lama identik dengan peradabannya masih tetap dipertahankan pada sekitar dua dekade setelah perang kemerdekaan. Perang mempertahankan harga diri bangsa itu turut menyaksikan perjuangan yang tak sedikit dari kota Palembang. Meski begitu, pasca era tersebut berlalu, masyarakat kota ini segera pulih dan dapat menjalani hidup termasuk dengan menikmati berbagai hiburan dan beraktifitas sesuai mata pencaharian masing-masing.
Kesadaran atas nasionalisme pun mengambil bentuk yang nyata di ibukota Sumatera Selatan, yang dibuktikan dengan harmonisme kehidupan antar-identitas di dalamnya. Penghayatan kepada kepercayaan / agama berjalan dengan baik, seturut dengan rasa persatuan yang membangun semangat masyarakat pasca perang tanpa adanya gesekan berarti. Tak terlihat polarisasi dari spektrum-spektrum pemikiran destruktif semisal “Islam vs Non-Islam” ataupun “Pribumi vs Pendatang”.
Palembang telah memiliki konstruk fisik eksisting bagi transportasi modern seperti pesawat maupun kereta api, bahkan jauh sebelum era kemerdekaan. Hal itu menandakan bahwa ibukota Sumatera Selatan tidak dapat mengelakkan dirinya dari kemajuan zaman yang terus bergulir. Intensitas interaksi dengan wilayah-wilayah lain, seperti Jawa dan bahkan Singapura dapat terbina dengan baik. Meski begitu, masyarakat Palembang tidak melupakan aspek terpenting dalam membangun peradaban, sehingga berkat kesadaran serta perjuangan, berdirilah instansi pendidikan yang begitu ikonik seperti Universitas Sriwijaya.
Sumber :
Ikhsan, Rd. Muhammad, Palembang dari Waktoe ke Waktu, Palembang : UNSRI Press, 2018. Hlm. 102-103.
Adiwikarta, M.D., Ilmu Bumi Sumatera dan Tanah Air Kita Indonesia, Cetakan Ke-22, Bandung : Penerbit Fa. Pustaka Star, 1961. Hlm. 49.
Op.Cit. Hlm. 108.
Soeroto, Suri-Teladan Tokoh-Tokoh Zaman Silam, Jakarta : Myrttle Publishing, 2004. Hlm. 21-22.
Op.Cit. Hlm. 103.
Sukijanto, dkk., Peringatan 20 Tahun Gereja Kristen Palembang “Siloam”, Palembang : Gereja Kristen Palembang “Siloam”, 1977. Hlm. 27.
Adiwikarta, M.D., Ilmu Bumi Sumatera dan Tanah Air Kita Indonesia, Cetakan Ke-22, Bandung : Penerbit Fa. Pustaka Star, 1961. Hlm. 49.
Meuraxa, Dada, Keradjaan Melaju Purba, Medan : Kalidasa, 1971. Hlm. 32.
Ibid. Hlm. 33.
Sulistyaningsih, Cahyo, M. Yusef Rizal, Profil Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya , Palembang : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, 2015. Hlm. 16.
Op.Cit.
Tim Penyusun, 30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964 , Jakarta : PT. Citra Lamtoro Gung Persada, 1986. Hlm. 211.
Nurhuda, Eko, “Bandara Talang Betutu Riwayatmu Kini…”, www.bungeko.com 2015.
Adiwikarta, M.D., Ilmu Bumi Sumatera dan Tanah Air Kita Indonesia, Cetakan Ke-22, Bandung : Penerbit Fa. Pustaka Star, 1961. Hlm. 50.
Ibid. Hlm. 48.
Meuraxa, Dada, Keradjaan Melaju Purba, Medan : Kalidasa, 1971. Hlm. 33.
Op.Cit. Hlm. 50.
Tim Penyusun Universitas Sriwijaya, Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Unsri 2011/2012, Palembang : Universitas Sriwijaya, 2011. Hlm. 1.