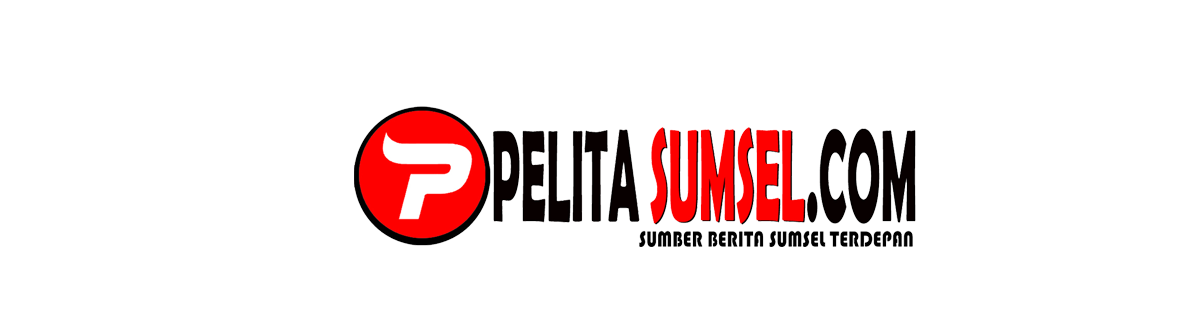Media Harus Mampu Membangun Kemandirian Relatif Terhadap Platfom Digital

Jakarta, Pelita Sumsel – Melalui buku “Dialektika Digital” yang ditulis Agus Sudibyo, dirinya menawarkan cara bagaimana media nasional mampu membangun
kemandirian relatif terhadap platform digital.
“Buku ini menawarkan bukan sikap anti platfom, bukan menolak transformasi
digital karena transformasi digital itu suatu keniscayaan yang tidak bisa
dihindari, namun bagaimana media nasional mampu membangun kemandirian
relatif terhadap platfom digital, kemandirian secara teknologi, secara bisnis dan
secara jurnalistik,” ungkap penulis buku “Dialektika Digital: Kolaborasi dan
Kompetisi Media Massa Vs Digital Platform”, Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo
dalam acara bedah buku yang digelar FMB9, Selasa (5/4/22).
Kemandirian relatif ini, jelas Agus, artinya tidak putus secara total dalam
menjalin kerja sama dengan platfom digital ini, namun sebuah sikap untuk tidak
terlalu tergantung pada paltfom dalam mendistribusikan konten, memproduksi
jurnalisme dan juga dalam berbisnis.
Namun kemandirian relatif ini, lanjut Agus menerangkan, juga harus didukung
dengan kebijakan yang memadai dari pemerintah.
Sehingga, lanjutnya, publisher right, serta undang-undang perlindungan data
pribadi, sosial media dan lain-lain yang dibuat oleh pemerintah adalah unsur-
unsur regulasi dimana negara hadir untuk menyehatkan ekosistem media dan
menjaga ruang publik yang beradab.
“Karena model periklanan yang didorong oleh platform ini menunjukan
bukanlah model periklanan yang bagus untuk ruang publik media, karena yang
menonjol adalah iklan-iklan yang jelek,” tutupnya.
Di era digital ini, media massa dituntut untuk menghadirkan informasi yang lebih
cepat, variatif, personal dan interaktif. Ketidakmampuan media konvensional
dalam memenuhi hal tersebut membuat masyarakat meninggalkannya dan
beralih ke platform digital.
Kehadiran platform digital global seperti google, facebook dan lain sebagainya
merupakan teman sekaligus lawan atau friend sekaligus enenemy bagi
masyarakat, utamanya mereka yang bergerak di media konvensional. Hal inilah
yang menyulitkan dalam menghadapi kehadiran platfom digital.
“Menghadapi platfom digital ini juga tidak gampang. Mereka adalah teman
sekaligus musuh (frenemy). Publisher dengan mereka hubungannya bukan
hanya kompetisi tapi juga coopertaion,” kata Agus di sela-sela pemaparannya.
Menurut Agus, kita tidak bisa mengelak bahwa jurnalis selaku publisher banyak
terbantu oleh platfrom-platform seperti google, facebook dan lainnya dalam
memproduksi konten dan mendistribusikan.
“Jadi ini yang susah, kalo mereka lawan seratus persen, itu mereka mudah
menghadapinya. Tetapi yang mereka lawan adalah musuh sekaligus teman. Ini
sulit dihadapi,” beber Agus.
Namun, Agus menjelaskan, dalam banyak data yang diperoleh, menunjukan
bahwa keberadaan serta kehadiran platform digital ini bersifat disruptif
terhadap daya hidup industri media massa konvensional.
“Dan bagaimana dalam keadaan, dalam ekosistem yang disruptif itu, industri
media massa di situ jurnalisme harus bisa bertahan hidup,” tutupnya
Sementara itu, Anggota BPIP Rikard Bagun yang hadir secara virtual, mengawali
pemaparannya dengan menyampaikan apresiasi atas diterbitkannya buku
berjudul “Dialektika Digital” ini.
Menurutnya, penulis buku ini sangat
dipengaruhi pemikiran hegelian.
“Jadi sampai pada suatu keinginan untuk berkolaborasi dan itulah sintesa. Bung
Agus mengatakan perlu sintesa atau bahasa bisnisnya itu kolaborasi,” kata
Rikard.
Pengaruh yang kedua, terang Rikard, adalah secara kultur. Menurutnya, penulis
buku ini sangat Bhineka Tunggal Ika. Bahwa kendati ada perbedaan, namun
disatukan dalam sebuah kerjasama.
“Jadi berbeda-beda tapi kita bisa disatukan dalam sebauh kerjasama. Tetapi
saya melihat, syarat-syarat kerjasamanya tidak terpenuhi. Karena apa, media
konvensional sudah dihajar habis oleh yang namanya gangguan dan guncangan
digital. Jadi digital disruption,” ungkap Rikard.
Rikard menjelaskan, digital tranformation atau transformasi digital bukan hanya
menyangkut bentuk atau form, namun juga isi atau konten.
“Dan seluruh ekosistem media konvensinal itu tidak hanya diganggu bahkan
boleh dikatakan dirusak,” tegasnya.
Ibarat sebuah kerajaan, konten adalah rajanya atau the king, sedangkan
distribusi dan periklanannya adalah sang ratu.
“Kalau industri media itu dianggap sebagai kerjaaan, maka content is the king itu
mengalami gangguan, disorientasi. Karena sekarang di sana bertaruh dengan
hoaks, fake news. Kalau rajanya sudah diganggu, kemudian kuenya juga
terganggu tinggal istananya,” terang Rikard.
Rikard lantas bertanya apakah kehadiran platfrom digital dapat berjalan paralel
dengan media konvesional? Sebab menurutnya, kalau berbicara kompentisi
media konvensinal selalu mengacu pada tiga prinsip dasar. Pertama adalah
rasionalitas tentang benar dan salah.
“Kedua adalah etika tentang baik dan buruk dan ketiga adalah estetika. Apakah
ada seni yang tidak vulgar? Karena di situlah daya sugesti,” imbuhnya.
Sementara di pihak lain, kata Rikard, kita melihat rasionalitas itu sudah digeser.
Dimana yang benar bisa disalahkan dan yang salah bisa dibenarkan. Kemudian
hoaks bisa diagungkan dan yang agung bisa di-hoaks-an.
“Lalu quantity is our quality. Jadi yang dikejar jumlah. Kemudian yang dikejar
adalah kecepatan. Jadi the survival is the fastest. Jadi siapa yang cepat dia yang
dapat,” tuturnya.
“Lalu digital dalam telaahan itu menghasilkan budaya dangkal. Dia tidak dapat
fokus karena ia bertarung dengan kecepatan. Dan tidak heran jika banyak orang
menggunakan sosial media untuk memperjuangkan ide-ide intoleran,”
tutupnya.