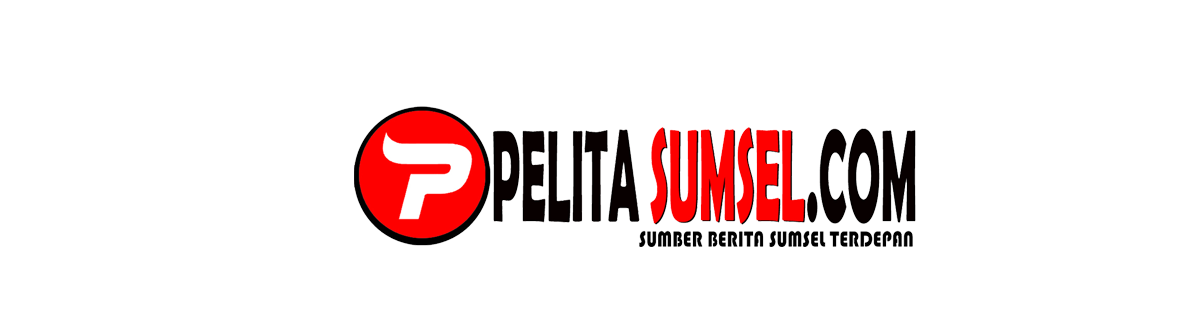Perlukah Dekonstruksi Instan Lembaga Pendidikan?

* oleh : Muhammad Kusairi (Penggiat Sosmed)
Hampir semua lini kehidupan, tak terkecuali dunia pendidikan, selalu ada yang namanya “trade off” atau kesenjangan. Ini sama ketika kita bicara soal pembangunan ekonomi. Juga ada yang namanya kesenjangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Istilah lain, ada yang menyebut kesenjangan antara “Das Sein” (Keharusan) dan “Das Shollen” (Kenyataan).
Apa yang disampaikan Menteri Pendidikan Nadiem, bahwa Gelar tidak menjamin Kompetensi, Kelulusan tidak menjamin kesiapan untuk Berkarya, dan Akreditasi tidak menjamin Mutu, secara kenyataan mungkin ada benarnya. Tapi untuk menguji kesahehan pernyataan itu harus dilakukan kajian, mengapa output atau outcome dunia pendidikan terjadi sebagaimana yang dikeluhkan. Kajian akademisnya perlu dibuat sehingga tidak ujug-ujug rubah kurikulum atau meniadakan Ujian Nasional (UN).
Pertanyaan berikut tentu tidak selesai pada soal retorika, tetapi apakah instrumen pendidikan yang bisa dijadikan substitusi dari gelar, kelulusan, dan akreditasi tersebut?
Mungkin benar, tidak sedikit keberhasilan seseorang, apakah dinilai dari sisi kekayaan, karya-karyanya maupun kiprahnya di masyarakat, yang berhasil dan melesat luar biasa, tanpa mensyaratkan tingkat pendidikan tertentu yang mumpuni. Tetapi itu bisa disebut sebagai “nasib baik” atau “garis tangan” saja yang dimiliki seseorang dan tidak bisa dijadikan bahan untuk men-generate semuanya. Apalagi secara instan mendekonstruksi sistem. Karena ibarat aplikasi, pendidikan tak sekadar hardware tapi software dan hardware, serta sistem yang mengoneksi keduanya.
Sama saja ketika kita mengambil contoh keberhasilan seorang bos facebook, Mark Zuckenberg atau Nadiem sendiri sebagai mantan CEO Gojek. Berbeda dengan Mark yang “DO” dari kampusnya, Nadiem justru sekolah serius di sekolah bergengsi di Amerika, Harvard University. Apakah lantas seorang lulusan Harvard harus mendekonstruksi kampus atau sekolahnya lantaran tidak semua lulusannya berhasil, misalnya? Kan tidak. Karena Das Sein sebuah kampus terkemuka di Amerika tidak seperti itu. Sama seperti ketika kita harus bicara di kampus-kampus terkemuka di Indonesia. Tidak semuanya berhasil. Sebaliknya, secara Das Shollen, tidak sedikit mereka yang sekolah di kampus-kampus biasa saja juga punya karya dan kiprah yang besar di masyarakat. Lalu kita mau pakai tolak ukur yang mana?
Jadi persoalan kompetensi, karya, dan mutu seseorang tidak sekadar karena favorit atau tidak favoritnya sekolah. Juga bukan karena hebat tidaknya seorang Menteri Pendidikan. Tetapi ada faktor lain, seperti keterampilan sosial, kemampuan membina jaringan, akseptabilitas terhadap sumber-sumber keuangan yang memungkinkan mereka bisa mengembangkan bisnis, fasilitasi atau mentor dari orang-orang hebat, dan dukungan struktural (negara) dalam memberikan ruang kemajuan dan kesempatan pada seseorang. Itu yang penting.
Bagi seorang yang dibesarkan dalam lingkungan orang-orang kaya atau mereka yang memiliki koneksi terhadap kekuasaan mungkin jalannya bisa lebih mudah. Tapi bagi mereka yang merangkak dari nol bahkan minus ini yang harus menjadi pusat perhatian. Di sinilah peran pendidikan atau lembaga pendidikan harus bisa dirasakan manfaatnya. Termasuk kepiawaian seorang Menteri Pendidikan. Barangkali. (*)